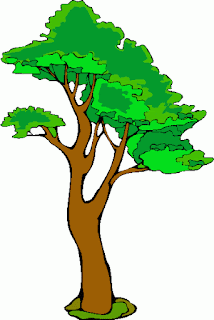Sebelum dia tidur, biasanya dia minta cerita tentang apa saja. Mulai dari cerita para nabi, dunia binatang hingga soal daun dan kerikil. Dus, saya harus pandai-pandai mengarang cerita yang tetap tidak saya biarkan konyol apalagi bohong meski tema yang dimintanya hanya masalah daun dan kerikil itu. Seperti semalam, dia minta diceritakan tentang kenapa ada duri pada daun nanas. Apa nggak puyeng menjawabnya!! Karena saya tak punya jawaban dan masih berusaha mendapatkannya, akhirnya saya yang balik bertanya dengan hal lain. Maka terciptalah tiga episode ini:
Episode I
"Kenapa kalau mau tidur harus berdoa?" tanya saya.
"Biar dapat pahala dan tidak diganggu setan," jawab anak saya.
"Bagus."
"Tapi harusnya kalau mau tidur itu bawa pedang-pedangan," kata dia.
"Loh, kenapa?" tanya saya.
"Biar bisa buat gelitiki ketek setannya. Lalu dia lari ketakutan. Iya, kan?"
"...:(... :)...."
Weh....setan ternyata punya ketek.
Episode II
"Yah, di laptop itu Raja Namrud katanya ada di kegelapan."
"Memang iya." jawab saya
"Kenapa?"
"Kenapa ayo?" saya balik tanya.
Dia diam sejenak. Lalu, "Soalnya di rumahnya tidak masang listrik."
Heemmmmzzz
Episode III
"Yah, setan itu makanannya apa sih?"
"Ya sama dengan kita. Kalau kita makan nasi tapi tidak berdoa, maka setan ikut makan."
"Oh, tak kira makan roti bakar."
"Roti bakar?" tanya saya agak terkejut.
"Iya, setan kan dibuat dari api, kan. Makanannya itu pasti dibakar kayak roti bakar. Nggak direbus."
Episode I
"Kenapa kalau mau tidur harus berdoa?" tanya saya.
"Biar dapat pahala dan tidak diganggu setan," jawab anak saya.
"Bagus."
"Tapi harusnya kalau mau tidur itu bawa pedang-pedangan," kata dia.
"Loh, kenapa?" tanya saya.
"Biar bisa buat gelitiki ketek setannya. Lalu dia lari ketakutan. Iya, kan?"
"...:(... :)...."
Weh....setan ternyata punya ketek.
Episode II
"Yah, di laptop itu Raja Namrud katanya ada di kegelapan."
"Memang iya." jawab saya
"Kenapa?"
"Kenapa ayo?" saya balik tanya.
Dia diam sejenak. Lalu, "Soalnya di rumahnya tidak masang listrik."
Heemmmmzzz
Episode III
"Yah, setan itu makanannya apa sih?"
"Ya sama dengan kita. Kalau kita makan nasi tapi tidak berdoa, maka setan ikut makan."
"Oh, tak kira makan roti bakar."
"Roti bakar?" tanya saya agak terkejut.
"Iya, setan kan dibuat dari api, kan. Makanannya itu pasti dibakar kayak roti bakar. Nggak direbus."
Label:
HARIANKU